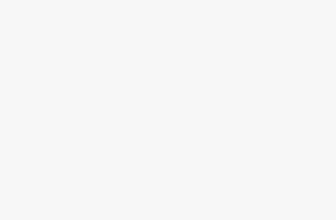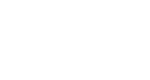Oleh : Saikhul Hadi – Penyuluh Jakarta Utara
Setiap kali peringatan HUT Kemerdekaan RI, selalu saja muncul pertanyaan retoris ini: sudahkah kita merdeka? Bahkan, ada lebih sinis: benarkah kita merdeka?
Menurut hemat saya, pertanyaan-pertanyaan di atas tidak harus serta dijawab, seperti layaknya cerdas cermat. Masing-masing orang punya persepsi tentang makna merdeka dan kemerdekaan.
Bagi bangsa Indonesia, arti merdeka ditahun 1945 adalah sikap mental kolektif bangsa untuk keluar dari zona kolonial bangsa asing. Penjajahan atau kolonialisme dibangun atas asumsi keagungan satu bangsa atas bangsa lain, sehingga, seolah punya hak untuk menginvasi dan menguasai. Oleh karena itu, sikap pendiri bangsa kita atas penjajahan sangat terang: tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Proklamasi kemerdekaan kemudian menjadi ‘jembatan’ yang menghubungkan sekaligus memisahkan. Kata Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas untuk Indonesia adil dan makmur, berdikari, dan berdaulat. Sebagai pemisah, kemerdekaan adalah garis demarkasi dari mental ‘budak di negeri sendiri’ menjadi mental ‘tuan di negeri sendiri’.
Berkah kemerdekaan sebagai jembatan masa depan sudah bisa kita rasakan saat ini. Lalu bagaimana dengan tuah kemerdekaan sebagai gunting pemutus mental ‘terjajah’ puluhan hingga ratusan tahun?
Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Jika kemudian dikaitkan dengan pertanyaan pembuka, mungkin yang dimaksud adalah sudahkah mental kita merdeka atau benarkah kita merdeka secara mental?
Beberapa tahun lalu, kita mendengar slogan Revolusi Mental yang digagas Presiden Joko Widodo. Saya kutip dari laman www.kominfo.go.id. Inilah ide dasar dari digaungkannya kembali gerakan revolusi mental oleh Presiden Joko Widodo. Jiwa bangsa yang terpenting adalah jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan. Jiwa merdeka disebut Presiden Jokowi sebagai positivisme. Gerakan revolusi mental semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah menghadapi tiga problem pokok bangsa yaitu; merosotnya wibawa negara, merebaknya intoleransi, dan terakhir melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional.
Masih relevankah bicara mental di HUT ke-79 RI? Hemat saya, tetap relevan dan akan selalu relevan. Membangun gedung megah, penting. Namun mendidik sumber daya manusia alias mental manusianya untuk mengelola gedung, juga sama pentingnya. Pembangunan jalan raya diperlukan. Membangun kerukunan umat beragama jangan diabaikan. Yang terakhir ini, menjadi salah satu tugas penyuluh agama.
Moderasi
Indonesia memilih tidak menjadi negara agama, sekaligus bukan negara sekuler. Pancasila dipilih sebagai dasar negara, dengan pengakuan Ketuhanan di sila pertama. Negara mengakui agama-agama dan melindungi umat beragama.
Pluralitas Indonesia bisa menjadi pisau bermata ganda jika tidak dikelola dengan bijaksana. Moderasi adalah jalan bijak dan bajik untuk konteks Indonesia. Pilar-pilar nilai moderasi bukan untuk mendegradasikan iman seseorang atau mengaburkan konsep ketuhanan. Moderasi adalah jalan raya yang memungkinkan semua orang bisa melewatinya tanpa cemas digilas atau dilibas. Kerukunan mutlak diperlukan, agar kemakmuran bisa dirasakan.
Peran Penyuluh Agama
Penyuluh agama membawa peran ganda. Pertama, sebagai agent of change mental dan mindset bangsa dengan membangun sisi rohani melalui sentuhan agama. Kita bangsa bermartabat yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kita punya budaya dan tradisi khas serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Penyuluh agama harus terus bersuara, agar kebaikan di masyarakat tetap terjaga.
Kedua, penyuluh agama sebagai pengawal bendera moderasi beragama. Program nasional ini menjadi isu strategis di tengah tantangan era disrupsi. Ada saja pihak yang ingin menjegal moderasi beragama dengan dalih-dalih agama. Oleh karena itu, program Kampung Moderasi menjadi signifikan sebab bisa menjadi benteng pengaman dari serangan ideologi yang merusak kerukunan bangsa.
Kedua tugas ini tidak ringan. Namun, kita selalu punya semangat, ‘Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’.